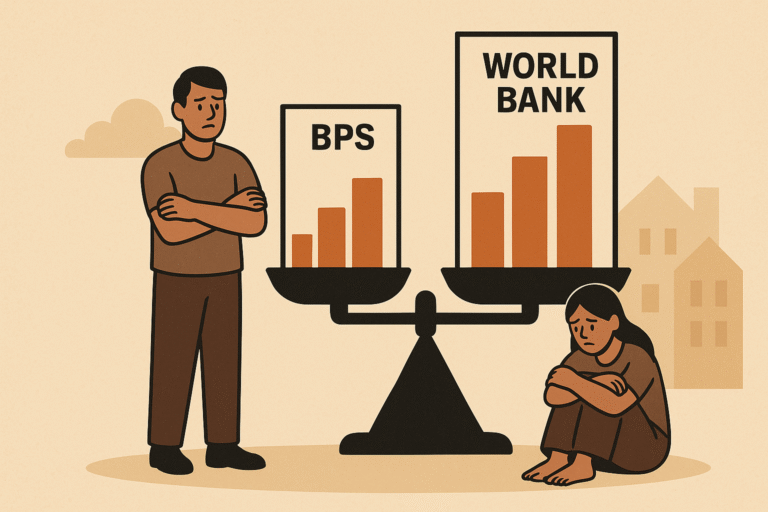Indonesia kembali dibuat geger oleh data terbaru World Bank dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Dalam grafik yang beredar luas di media sosial, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia dalam jumlah penduduk miskin, yakni 60,3 persen.
Lebih tinggi dari El Salvador, Brazil, bahkan Iran. Di atas Indonesia hanya ada Zimbabwe—negara yang selama ini identik dengan inflasi gila-gilaan dan keruntuhan ekonomi.
Sontak, grafik ini memicu perdebatan. Banyak pihak membandingkannya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara resmi mencatat tingkat kemiskinan nasional per Maret 2024 berada di angka 9,36 persen. Perbedaan ini bukan hanya mencolok—tapi juga membuka ruang pertanyaan kritis: Siapa yang harus dipercaya?
Pertama, mari kita bedah definisinya. BPS menggunakan indikator pendapatan garis kemiskinan nasional, yang pada Maret 2024 setara dengan Rp535.547 per kapita per bulan. Siapa pun yang hidup di bawah angka ini dianggap miskin.
Sementara World Bank menggunakan standar internasional, yaitu US$3,65 per hari (kira-kira Rp1,7 juta per bulan per kapita) untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah seperti Indonesia.
Dari sini terlihat bahwa World Bank memakai standar yang lebih tinggi dan kontekstual secara global. Seseorang yang menurut BPS sudah keluar dari kategori miskin, bisa jadi menurut World Bank justru masih jauh dari kehidupan layak.
Kedua, soal metode. BPS mengambil data dari survei SUSENAS dengan pendekatan konsumsi dan pengeluaran. World Bank menggabungkan berbagai sumber, termasuk makroekonomi dan model statistik, lalu mengkalibrasinya dengan paritas daya beli antarnegara. BPS lebih cermat di tingkat mikro; World Bank lebih tajam untuk komparasi antarnegara.
Namun yang menarik bukan sekadar teknis statistik. Melainkan narasi yang dibangun darinya. Pemerintah tentu lebih nyaman mengacu pada data BPS. Angka 9 persen terasa lebih ‘bersahabat’ untuk politik pencitraan dan stabilitas.
Tapi World Bank—sebagai lembaga internasional yang tidak tunduk pada logika politik lokal—lebih independen dalam menyuarakan potret kemiskinan struktural yang sering tersembunyi.
Sementara itu, fakta-fakta pendukung juga menggambarkan betapa ketimpangan masih besar. Gini ratio Indonesia 2024 berada di angka 0,379—cukup tinggi dibanding negara ASEAN lain. Rata-rata upah buruh hanya Rp3,27 juta per bulan. Di Jakarta, biaya sewa kos dan makan sederhana saja sudah bisa menghabiskan itu.
Di sisi lain, laporan Oxfam menyebut kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan harta 100 juta orang termiskin. Jadi, meskipun angka makro ekonomi seperti pertumbuhan GDP menyentuh 5 persen, kenyataannya distribusinya sangat timpang.
Perlu juga dipahami, angka kemiskinan rendah bukan berarti kemakmuran tinggi. Bisa saja banyak orang tidak miskin versi BPS, tapi juga tidak sejahtera versi realitas: hidup pas-pasan, tanpa tabungan, tanpa akses kesehatan, dan tanpa jaminan pensiun.
Secara sosial dan budaya, hal ini menciptakan kelompok “hampir miskin”—kelas rapuh yang mudah jatuh miskin karena satu musibah saja. Sakit, PHK, atau inflasi bahan pokok sudah cukup untuk menjungkirbalikkan hidup mereka.
Secara hukum dan kebijakan, banyak program bansos justru bersifat tambal sulam. Alih-alih membangun kemandirian ekonomi rakyat, justru memperkuat ketergantungan pada negara.
Di tengah semua ini, pemerintah sering kali menyalahkan persepsi publik. Tapi bagaimana bisa menyalahkan rakyat yang kecewa jika keseharian mereka diwarnai PHK, harga kebutuhan pokok yang melambung, dan fasilitas publik yang stagnan?
Yang dibutuhkan bukan perdebatan soal “versi siapa yang benar”. Tapi keberanian mengakui bahwa kemiskinan di Indonesia adalah masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyisir statistik yang menyenangkan.
Jadi, data mana yang lebih valid?
Secara politik, data BPS sahih sebagai rujukan resmi negara. Tapi secara moral dan substansi, World Bank memberikan gambaran yang lebih jujur soal betapa banyak warga Indonesia yang belum hidup layak, meski mereka tidak tercatat sebagai ‘miskin’ di statistik lokal.
Data World Bank juga penting sebagai pengingat keras: bahwa kemiskinan bukan sekadar ukuran konsumsi, tapi tentang akses, kualitas hidup, dan martabat manusia.
Kesimpulannya, tidak ada gunanya menolak data World Bank jika faktanya kita semua tahu: banyak keluarga masih harus memilih antara makan dan bayar sekolah; antara kerja lembur atau menebus obat. Pemerintah perlu berhenti bersembunyi di balik persentase kecil.
Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar klaim sukses statistik, tapi perubahan nyata di dapur mereka.