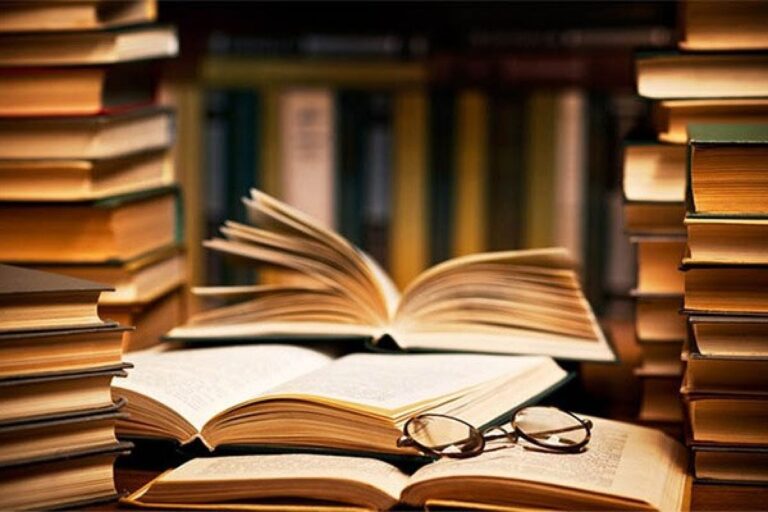Indonesia memiliki lebih dari 24.000 jurnal terdaftar di platform GARUDA. Angka ini seharusnya mencerminkan kemajuan pesat dunia akademik nasional. Namun, kenyataan menunjukkan ironi: hanya sekitar 0,055% dari jurnal tersebut yang masuk kategori Q1 Scopus, salah satu standar global untuk jurnal berkualitas. Angka ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kita terlalu sibuk memperbanyak jurnal sehingga lupa memperbaiki kualitasnya?
Kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab. Regulasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadikan publikasi jurnal sebagai indikator utama kinerja dosen. Tridharma Perguruan Tinggi menempatkan penelitian dan publikasi di jurnal ilmiah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai respons, banyak universitas mendirikan jurnal sendiri untuk menampung publikasi dosennya. Namun, langkah ini lebih terlihat seperti upaya administratif semata daripada inisiatif untuk membangun ekosistem ilmiah yang bermutu.
Dari 24.684 jurnal di Indonesia, hanya 163 yang terindeks Scopus. Jumlah ini tidak sebanding dengan usaha besar yang telah dikerahkan untuk mendirikan begitu banyak jurnal. Apalagi jika dilihat dari segi kualitas, jurnal Indonesia yang masuk kategori Q1 sangat minim, bahkan kurang dari 20. Kenyataan ini mencerminkan bahwa jurnal-jurnal kita belum memiliki daya saing di tingkat internasional. Penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian pada manajemen jurnal, proses editorial, dan kualitas artikel yang diterbitkan.
Banyak jurnal dikelola oleh dosen yang memiliki tanggung jawab utama sebagai pengajar dan peneliti. Posisi sebagai pengelola jurnal sering kali dianggap sebagai tugas tambahan yang dilakukan dengan sumber daya seadanya. Akibatnya, standar pengelolaan seperti peer review yang ketat atau proses editorial yang profesional sering diabaikan. Lebih jauh lagi, artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal tersebut sering kali belum memenuhi standar substansi ilmiah internasional, baik dari segi kebaruan temuan maupun metodologi yang digunakan.
Dominasi Scopus dalam pengindeksan jurnal juga menjadi isu tersendiri. Scopus dianggap sebagai simbol kredibilitas dan kualitas internasional. Banyak dosen berlomba-lomba mempublikasikan artikel di jurnal yang terindeks Scopus demi meningkatkan reputasi akademik mereka. Namun, orientasi ini sering kali berujung pada penerbitan yang hanya mengejar kuantitas, tanpa memperhatikan relevansi atau dampak penelitian tersebut terhadap masyarakat. Padahal, Indonesia memiliki sistem pengindeks lokal, yakni SINTA (Science and Technology Index), yang seharusnya dapat diberdayakan untuk mendorong jurnal-jurnal nasional agar lebih kompetitif di tingkat global.
SINTA, yang mengakreditasi jurnal mulai dari level regional hingga internasional, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pengindeks yang diakui. Jika pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas SINTA setara dengan Scopus atau Web of Science, ketergantungan akademisi Indonesia pada pengindeks internasional dapat dikurangi. Selain itu, berfokus pada SINTA juga dapat memperkuat ekosistem penelitian lokal karena dana yang digunakan untuk penelitian dan publikasi tetap berputar di dalam negeri.
Namun, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu solusi. Universitas dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi akar masalah yang ada. Misalnya, pengelolaan jurnal sebaiknya tidak dibebankan kepada dosen aktif. Sebaliknya, pengelolaan ini dapat dilakukan oleh badan penerbit independen yang didedikasikan untuk menjaga profesionalisme dan kualitas jurnal. Dengan demikian, jurnal dapat dikelola secara lebih fokus tanpa terpengaruh oleh tugas utama dosen.
Selain itu, pelatihan intensif bagi pengelola jurnal menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis seperti tata kelola dan proses editorial, tetapi juga etika publikasi dan strategi internasionalisasi. Dengan adanya pelatihan, pengelola jurnal dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan memenuhi standar internasional.
Pemerintah juga perlu memberikan dukungan finansial yang memadai untuk pengelolaan jurnal. Hibah yang diberikan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan, dengan tujuan meningkatkan kualitas jurnal secara menyeluruh. Dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur penerbitan, memperbaiki sistem peer review, atau membantu jurnal lokal masuk ke pengindeks global seperti DOAJ atau PubMed.
Namun, di atas semua itu, paradigma tentang publikasi ilmiah perlu diubah. Penilaian kinerja akademisi tidak boleh hanya berfokus pada jumlah publikasi di jurnal terindeks Scopus, tetapi juga pada dampak penelitian terhadap masyarakat. Dengan demikian, kualitas dan relevansi penelitian menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam dunia akademik global. Saatnya ini puluhan ribu jurnal itu banyak namun seperti buih.
Dengan memperbaiki sistem pengelolaan jurnal, memberdayakan pengindeks lokal seperti SINTA, dan mendorong akademisi untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, kita dapat membangun ekosistem ilmiah yang kompetitif. Ini bukan hanya tentang meningkatkan jumlah jurnal yang terindeks Scopus, tetapi juga tentang menciptakan penelitian yang benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
Pada akhirnya, fokus kita seharusnya bukan pada seberapa banyak jurnal yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar kontribusi jurnal-jurnal tersebut terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat. Indonesia harus berani keluar dari jebakan “kuantitas tanpa kualitas” dan mulai membangun tradisi akademik yang berorientasi pada mutu dan keberlanjutan.